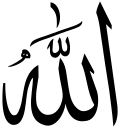Sunni
Sunni (/ˈsuːni, ˈsʊni/, KBBI: Suni) adalah cabang (firkah) terbesar Islam, yang dianut 85–90% populasi penduduk Muslim. Namanya berasal dari kata Sunnah, yakni meneladani apa yang telah diajarkan Nabi Islam Muhammad.[1] Perbedaan Sunni dengan Syiah berkaitan dengan pertentangan tentang siapa yang pantas sebagai penerus Muhammad yang berujung pada perbedaan antara akidah dan fikih.[2] Menurut tradisi Sunni, Muhammad tidak memiliki penerus dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Saqifah menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah.[2][3][4] Hal ini berbeda dengan pandangan Syiah, yang menganggap bahwa Muhammad menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penerusnya.[5] Orang yang menganut cabang Islam ini lebih menyebut dirinya sebagai "ahli sunah", atau lebih lengkapnya ahlussunnah wal-jamāʻah ("orang yang mengikuti Sunnah dan berada dalam golongan Jamaah"). Pengikut dari ahlus-sunnah dikenal dengan sebutan Sunni. Sunni sering dijuluki sebagai "Islam Ortodoks",[6][7][8] meski banyak ulama dan pakar agama menentangnya.[9] Al-Qur'an dan hadis (utamanya yang berada dalam Kutubussittah) dan ijma', menjadi landasan fikih Sunni. Syariah diturunkan dengan mempertimbangkan sumber-sumber tersebut, bersama dengan qiyas, istislah, dan istihsan, menggunakan metode ijtihad yang dikembangkan imam-imam mazhab. Terkait dengan akidah, Sunni berpegang teguh pada rukun iman. Terdapat dua golongan mazhab akidah dalam tradisi Sunni, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menganut pemahaman ilmu kalam, serta Atsariyah yamg menganut pemikiran tekstual. TerminologiSunnahSunnah, secara bahasa bermakna "jalan, cara, atau perilaku walaupun tidak diridai".[10] Kata bahasa Arab sunnah sudah tua dan berakar pada bahasa pra-Islam. Kata tersebut merujuk pada tradisi yang diikuti mayoritas orang.[11] Istilah tersebut mendapat signifikansi politik yang lebih besar setelah pembunuhan Khalifah ketiga Utsman bin ʿAffan . Dikatakan Malik al-Asytar, seorang sahabat terkenal Ali bin Abi Thalib, didorong selama pertempuran Shiffin melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah pertempuran usai, dirumuskan bagaimana "Sunnah yang benar sebagai alat pemersatu umat, bukan pemecah belah umat" (as-sunna al-ʿādila al-jāmiʿa gairal-mufarriqah) untuk menyelesaikan konflik. Waktu ketika sunnah adalah bentuk pendek dari “sunnah nabi” masih belum diketahui.[12] Pada masa Kekhalifahan Umayyah, gerakan politik seperti Syiah dan Khawarij yang memberontak terhadap pembentukan negara; memimpin pertempuran mereka atas nama "kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya".[13] Selama Perang Saudara Islam Kedua (680–92), istilah sunnah menerima konotasi yang kritis terhadap doktrin Syi'ah. Hal ini dicatat oleh Masrūq bin al-Ajdaʿ (w. 683), yang merupakan seorang Mufti Kufah, bahwa dua khalifah pertama, Abū Bakar ash-Shiddiq dan ʿUmar bin Khattab wajib dicintai dan diakui prioritasnya (Fadā'il). Seorang murid Masruq, asy-Sya'bi (meninggal antara 721 dan 729), yang awalnya memihak Syiah di Kufah selama Perang Saudara, tetapi membelot karena fanatisme mereka dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Khalifah Umayyah ʿAbdul-Malik bin Marwan, mempopulerkan konsep sunnah.[14] Juga diriwayatkan oleh asy-Sya'bi, bahwa dia mengutuk orang-orang yang membenci ʿAisyah dan menganggapnya sebagai pelanggaran sunnah.[15] Istilah sunnah berbeda dengan frasa yang lebih panjang panjang ahlussunnah wal-jamāʻah atau ahlussunnah, karena kedua tersebut relatif lebih muda. Kemungkinan merujuk kepada Ibnu Taimiyyah, yang menggunakan bentuk pendek tersebut untuk pertama kalinya.[16] Kemudian dipopulerkan oleh ulama pan-Islam seperti Muhammad Rasyid Ridha dalam risalahnya as-Sunnah wasy-Syiʿah au al-Wahhābīyah war-Rāfiḍah: Ḥaqāʾiq Dīnīya Taʾrīḫīyah Ijtimaʿīyah Iṣlaḥīyah ("Sunnah dan Syiah, atau Wahhabisme dan Rafidhah: Sejarah, Fakta Sosiologis, dan Orientasi Reformasinya“) yang diterbitkan pada tahun 1928–29.[17] Istilah "sunnah" biasanya sering digunakan dalam wacana Arab sebagai sebutan bagi Muslim Sunni, serta untuk membedakannya dengan Syiah. Pasangan kata "Sunnah-Syiah" juga digunakan dalam literatur penelitian Barat untuk menunjukkan kontras Sunni-Syiah.[18] AhlussunnahAhl berarti "keluarga-keluarga, pengikut, penduduk." Dengan demikian ahlussunnah berarti "orang yang mengikuti Sunnah."[19] Salah satu dokumen pendukung paling awal untuk ahlussunnah berasal dari sarjana Bashrah, Muhammad bin Siri (wafat 728). Namanya disebutkan dalam Shahih Muslim bin al-Hajjaj: "Sebelumnya seseorang tidak bertanya tentang sanad. Tetapi saat fitnah bermula, seseorang berkata: 'Sebutkan kami perawi Anda'. Seseorang kemudian akan menjawabnya: jika mereka adalah ahlussunnah, terimalah hadis mereka. Namun jika mereka adalah ahlul-bid'ah, tolaklah hadis mereka."[20] G.H.A. Juynboll menduga, istilah fitnah dalam pernyataan ini tidak terkait dengan Perang Saudara pertama (665–661) setelah pembunuhan Utsman bin Affan, tetapi Perang Saudara kedua (680–692)[21] ketika umat Islam terpecah. menjadi empat pihak (Abdullah bin Zubair, Bani Umayyah, Syiah di bawah al-Mukhtar bin Abi Ubaid, dan Khawarij). Istilah ahlussunnah ditunjuk dalam situasi ini yang menjauh dari ajaran sesat dari berbagai pihak yang bertikai.[22] Istilah ahlussunnah selalu dipuji. Abu Hanifah (w. 769), menegaskan bahwa orang-orang ini adalah "orang-orang saleh dan orang-orang Sunnah" (ahlul-ʿadl wa-ahlus-sunnah).[23] Menurut Josef van Ess istilah ini tidak berarti lebih dari "orang beriman yang terhormat dan benar".[24] Di kalangan mazhab Hanafi, sebutan ahlus-sunnah dan ahlul-ʿadl (orang-orang terhormat) dapat dipertukarkan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu ulama mazhab Hanafi, Abul-Qāsim as-Samarqandī (w. 953), yang menyusun katekismus untuk Samaniyah, terkadang menggunakan satu ungkapan dan terkadang ungkapan lain untuk kelompoknya sendiri.[25] Bentuk tunggal dari ahlus-sunna adalah ṣāḥib sunnah (individu pengikut sunnah).[26] Ungkapan ini digunakan misalnya oleh ʿAbdallāh bin al-Mubārak (w. 797) untuk seseorang, yang berlepas diri dari ajaran Syiah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah.[27] Selain itu, kata sifat nisbah sunni juga digunakan untuk individu. Demikian tercatat, ulama Quran dari Kufah Abu Bakar bin 'Auyasy (wafat 809) ditanya, bagaimana dia menjadi seorang sunni. Ia menjawab, "Orang yang, ketika firkah-firkah sesat disebutkan, tidak tertarik mengikutinya."[28] Ulama Andalusia, Ibnu Hazm (w. 1064) kemudian mengajarkan, bahwa mereka yang mengaku Islam dapat dibagi menjadi empat kelompok: Ahlussunnah, Muktazilah, Murji'ah, Syiah, dan Khawarij.[29] Pada abad ke-9, sejumlah orang mulai menambah istilah ahlussunnah dengan tambahan-tambahan positif lainnya. Abu al-Hasan al-Asy'ari merumuskan frasa untuk kelompoknya seperti seperti ahlussunnah wal-istiqāmah ("orang-orang yang mengikuti Sunnah dan teguh pendiriannya"), ahlussunnah wal-ḥadīṡ "orang-orang yang mengikuti Sunnah dan Hadis"),[30] atau ahlul-ḥaqq was-sunnah[31] (“orang-orang yang benar dan mengikuti Sunnah”). Ahlussunnah wal-jama'ahAl-Jama'ah, berasal dari kata al-jam'u artinya mengumpulkan sesuatu, dengan mendekatkan sebagian ke sebagian lain, atau mengumpulkan yang bercerai-berai. Kata jama'ah juga berasal dari kata ijtima' (perkumpulan), yang merupakan lawan kata tafaruq (perceraian) dan lawan kata dari furqah (perpecahan). Jama'ah adalah sekelompok orang banyak dan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan. Selain itu, Jama'ah juga berarti kaum yang bersepakat dalam suatu masalah, atau orang-orang yang memelihara kebersamaan dan kolektifitas dalam mencapai satu tujuan.[32] Kemunculan ungkapan ahlussunnah wal-jama'ah tidak sepenuhnya jelas. Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mūn (memerintah tahun 813–33) mengeluarkan dekrit tentang sekelompok orang, yang mengaku teguh kepada sunnah (nasabū anfusahum ilās-sunnah) dan mengeklaim, mereka adalah "orang-orang pengikut kebenaran, agama dan masyarakat” (ahlul-ḥaqq wad-dīn wal-jamāʿah).[33] Sunnah dan jama'ah sudah terhubung di sini. Sebagai pasangan, istilah-istilah ini sudah muncul pada abad ke-9. Tercatat bahwa murid Ahmad bin Hanbal, Harb bin Ismail (wafat 893) menulis kitab berjudul as-Sunnah wal-Jamāʿah, yang kemudian dibantah oleh ulama Muktazilah, Abu Al-Qasim al-Balkhi.[34] Al-Jubba'i (w. 916) mengisahkan dalam Kitāb al-Maqālāt nya, bahwa Ahmad bin Hanbal menggelari murid-muridnya dengan predikat sunnah wal-jama'ah.[35] Hal ini menunjukkan bahwa pengikut mazhab Hambali adalah yang pertama kali menggunakan frasa ahlus-sunnah wal-jamāʿah sebagai sebutan diri.[36] Akan tetapi, kelompok Karramiyyah yang didirikan oleh Muhammad bin Karram (wafat 859) mengklaim sebagai as-sunnah wal-jama'ah. Mereka menyebut itu karena mereka memuji pendiri mazhab ini setelah memahami sebuah hadis, yang menurutnya nabi Muhammad menubuwatkan bahwa pada akhir zaman akan muncul seorang laki-laki bernama Muhammad bin Karram, yang akan memulihkan sunnah dan jamāʿah dan berhijrah dari Khorasan ke Yerusalem, seperti ketika Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah.[36] Menurut kesaksian ulama Transoksiana, Abul-Yusr al-Bazdawi (w. 1099), Kullabiyah (pengikut ulama Basrian bin Kullab (w. 855)) juga mengeklaim sebagai ahlus-sunnah wal-jama'ah.[37] Abu al-Hasan al-Asy'ari jarang menggunakan ungkapan ahlus-sunna wal-jama'ah,[38] dan lebih menyukai kombinasi yang lain. Belakangan orang-orang Asy'ariyah seperti al-Isfaranini (w. 1027) dan Abdul-Qahir al-Baghdadi (w. 1078) juga menggunakan ungkapan ahlussunnah wal-jama'ah dan menggunakannya dalam karya-karya mereka untuk merujuk pada mazhab mereka sendiri.[39] Menurut al-Bazdawi semua orang Asy'ari pada masanya mengatakan mereka termasuk ahlus-sunnah wal-jama'ah.[37] Selama ini, istilah tersebut telah digunakan sebagai sebutan diri oleh pengikut Maturidi dan Hanafi di Transoksiana, serta sering digunakan oleh Abu al-Laits as-Samarqandi (wafat 983), Abu Syakur (wafat 1086) dan al-Bazdawi.[25] Mereka menggunakan istilah itu untuk melawan musuh mereka,[40] seperti pengikut Muktazilah.[41] Al-Bazdawī juga membedakan ahlussunnah wal-jama'ah dengan ahli hadis, "karena mereka akan menganut ajaran yang bertentangan dengan Al-Qur'an".[42] Menurut Syamsuddin al-Maqdisī (hidup akhir abad ke-10), ungkapan ahlussunnah wal-jama'ah menjadi pujian pada masanya, mirip dengan ahlul-ʿadl wat-tauḥīd ("orang-orang yang mengikuti keadilan dan tauhid"), yang digunakan untuk Muktazilah atau sebutan umum seperti Mukminun (“Orang Beriman“) atau aṣḥābul-hudā (“orang-orang yang mendapat petunjuk”) untuk orang Muslim, yang dipandang sebagai orang-orang beriman yang benar.[43] Karena ungkapan ahlussunnah wal-jama'ah digunakan dengan tuntutan keyakinan yang benar, maka dalam penelitian akademis digunakan istilah yang diterjemahkan sebagai "ortodoks".[44] Mengenai apa sebenarnya istilah jama'ah dalam frasa ahlussunnah wal-jama'ah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ath-Thahawi (wafat 933), dalam rangkumannya terhadap akidah Sunni, istilah jama'ah berbeda dengan istilah Arab furqah ("golongan yang berpecah belah").[45][46] Ath-Thahawi menjelaskan bahwa kata jama'ah dianggap benar dan lurus (ḥaqq wa-ṣawāb) dan furqah sebagai menyimpang dan menyesatkan (zaig wa-ʿaḍāb).[47] Ibnu Taimiyyah berpendapat, bahwa jama'ah sebagai lawan kata dari firqah mengandung makna ijtimāʿ ("kesepakatan bersam"). Selanjutnya ia menghubungkannya dengan prinsip ijmak, sumber hukum ketiga Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah.[48] Ulama Utsmaniyah Muslih ad Din al-Qastallani (wafat 1495) berpendapat bahwa jama'ah berarti "jalan para Sahabat” (ṭarīqat aṣ-ṣaḥābah).[49] Teolog Indonesia modern Nurcholish Madjid (w. 2005) menafsirkan jamaah sebagai konsep inklusif: terbuka untuk pluralisme dan dalam dialog tetapi tidak terlalu menekankan.[50] Sejarah Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah berasumsi bahwa Islam Sunni mewakili Islam normatif yang muncul selama periode setelah kematian Muhammad, dan bahwa Sufisme dan Syiah bercabang dari Islam Sunni.[51] Persepsi ini sebagian disebabkan oleh ketergantungan pada sumber-sumber yang sangat ideologis yang telah diterima sebagai karya sejarah yang dapat diandalkan, dan juga karena sebagian besar umat Islam adalah Sunni. Baik Sunni maupun Syiah adalah produk akhir dari persaingan antara ideologi selama beberapa abad. Kedua firkah tersebut menggunakan satu sama lain untuk memperkuat identitas dan doktrin mereka sendiri.[52] Empat khalifah pertama yang dikenal di kalangan Sunni dikenal sebagai Khulafaurrasyidin. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, dan keempat Ali.[53] Sunni mengakui penguasa setelahnya sebagai khalifah, meski mereka tidak memasukkan siapa pun dalam daftar Rasyidin setelah kematian Ali, hingga kekhalifahan secara konstitusional dihapuskan di Turki pada 3 Maret 1924. Transisi kekhalifahan menjadi dinasti monarkiBenih transisi kekhalifahan menjadi monarki kedinastian telah muncul, seperti yang ditakutkan oleh khalifah kedua Umar, sejak rezim khalifah ketiga Utsman, yang mengangkat banyak kerabatnya dari klan Bani Umayyah, seperti Marwan bin al-Hakam dan Walid bin Uqbah pada jabatan-jabatan penting di pemerintahan, sehingga menjadi penyebab utama kekacauan yang mengakibatkan pembunuhan dan pertikaian berikutnya selama masa Ali dan pemberontakan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, salah satu kerabat Utsman. Hal ini menyebabkan pembentukan pemerintahan kedinastian yang kuat dari Bani Umayyah setelah Husain, putra bungsu Ali dari Fatimah az-Zahra, gugur dalam Pertempuran Karbala. Bangkitnya kekuasaan Bani Umayyah, suku elite Makkah yang menentang keras Muhammad di bawah kepemimpinan Abu Sufyan, ayah Muawiyah, hingga penaklukan Makkah oleh Muhammad, sebagai penggantinya dengan diangkatnya Utsman sebagai khalifah, yang semula dihuni masyarakat egaliter yang muncul sebagai hasil revolusi Muhammad, berubah menjadi masyarakat yang terstratifikasi antara yang kaya dan yang miskin sebagai akibat dari nepotisme, dan dalam kata-kata El-Hibri melalui "penggunaan pendapatan zakat untuk menyubsidi kepentingan keluarga, yang dibenarkan Utsman sebagai ash-shilah".[54][55][56] Ali, selama masa pemerintahannya yang agak singkat, berupaya untuk mengembalikan sistem egaliter dan supremasi hukum atas penguasa yang dicita-citakan dalam dakwah Muhammad, tetapi terus menghadapi tentangan, dari perang Jamal melawan Aisyah, Thalhah, dan Zubair; perang Shiffin melawan Muawiyah; dan akhirnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Setelah Ali dibunuh, para pengikutnya segera memilih Hasan bin Ali putra sulung Ali dari Fatimah untuk menggantikannya. Hasan kemudian menandatangani perjanjian dengan Muawiyah melepaskan kekuasaan demi yang terakhir, dengan syarat antara lain, bahwa salah satu dari dua yang akan hidup lebih lama dari yang lain akan menjadi khalifah, dan bahwa khalifah ini tidak akan menunjuk seorang penerus tetapi akan meninggalkan soal pemilihan khalifah kepada publik. Selanjutnya, Hasan diracun sampai mati dan Muawiyah menikmati kekuasaan yang tak tertandingi. Tidak menghormati perjanjiannya dengan Hasan, ia mencalonkan putranya Yazid untuk menggantikannya. Setelah kematian Muawiyah, Yazid meminta Husain, adik laki-laki Hasan, putra Ali dan cucu Muhammad, untuk memberikan kesetiaannya kepada Yazid, yang ditolaknya dengan jelas. Kafilahnya dikepung oleh tentara Yazid di Karbala dan dia dibunuh bersama semua rekan prianya – total 72 orang, dalam pertempuran sehari penuh setelah Yazid memantapkan dirinya sebagai penguasa, meskipun pemberontakan publik yang kuat meletus setelah kematiannya melawan dinastinya untuk membalas dendam, tetapi Bani Umayyah mampu dengan cepat menekan mereka semua dan memerintah dunia Muslim, hingga akhirnya digulingkan oleh Bani Abbās.[57][58][59][60] Kekhalifahan dan monarki Bani AbbasKekuasaan dan "kekhalifahan" Bani Umayyah berakhir di tangan Bani Abbas, yang merupakan cabang dari Bani Hasyim, suku Muhammad, hanya untuk mengantarkan monarki dinasti lain yang disebut sebagai kekhalifahan dari tahun 750 M. Periode ini adalah masa-masa formatif Islam Sunni dengan lahirnya empat mazhab dari para fukaha: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, begitu juga Jafar ash-Shadiq yang menguraikan doktrin imamah, dasar pemikiran keagamaan Syiah. Tidak ada rumusan yang diterima dengan jelas untuk menentukan suksesi kekhalifahan Abbasiyah. Dua atau tiga putra atau kerabat lain diusulkan sebagai calon pemimpin baru, masing-masing didukung oleh partai pendukungnya sendiri. Uji kepatutan terjadi, dan pihak yang paling kuat menang serta mengharapkan bantuan dari khalifah yang mereka dukung begitu dia diangkat sebagai khalifah. Kekhalifahan dinasti ini berakhir dengan wafatnya Khalifah al-Ma'mun pada tahun 833 M, ketika periode dominasi Turki dimulai.[61] Pada zaman modernSetelah Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah, sebuah kekhalifahan Sunni terbesar selama enam abad, runtuh dan menandai berakhirnya kekhalifahan. Hal ini menyebabkan protes Sunni di tempat-tempat yang jauh termasuk Gerakan Khilafat di India, yang kelak memperoleh kemerdekaan dari Inggris serta terbagi menjadi Pakistan yang didominasi Sunni dan India yang sekuler. Pakistan, negara Sunni terpadat, kemudian dipisah menjadi Pakistan dan Bangladesh. Runtuhnya kekhalifahan tersebut juga mengakibatkan lahirnya Arab Saudi, sebuah monarki absolut berbasis dinasti yang terus memperjuangkan doktrin reformis Muhammad bin Abdul-Wahhab.[62][63][64][65] Hal ini juga dibarengi oleh berkembangnya gerakan Wahhabi, Salafiyah, Islamisme, dan Jihadisme yang memperjuangkan doktrin Ibnu Taimiyyah (1263–1328 M/661–728 H), seorang ulama Hambali. Perang Dingin mengakibatkan radikalisasi para pengungsi Afganistan di Pakistan yang berjuang melawan komunisme yang didukung pasukan Uni Soviet di Afganistan, sehingga lahirlah gerakan Taliban. Setelah jatuhnya rezim komunis di Afganistan dan perang saudara, Taliban merebut kekuasaan dari faksi Mujahidin di Afganistan dan membentuk pemerintahan di bawah kepemimpinan Mohammed Omar, yang disebut sebagai Amirul-Mukminin, cara yang terhormat untuk menyapa khalifah. Taliban diakui oleh Pakistan dan Arab Saudi hingga setelah Serangan 11 September 2001, yang diotaki oleh Usamah bin Ladin—seorang warga negara Saudi yang mendapat suaka oleh Taliban—terjadi, memantik perlawanan terhadap teror, termasuk melawan Taliban.[66][67][68] Pada abad ke-20, telah banyak kebencian di beberapa kalangan komunitas Sunni karena hilangnya keunggulan di beberapa wilayah yang sebelumnya didominasi Sunni seperti Syam, Mesopotamia, Balkan, Kaukasus Utara, dan anak benua India.[69] Upaya terbaru oleh kelompok radikal jihadisme salafi untuk mendirikan kembali kekhalifahan Sunni terlihat dalam munculnya kelompok militan NIIS, dengan pemimpinnya Abu Bakar al-Baghdadi yang dikenal di kalangan pengikutnya sebagai khalifah dan Amirulmukminin, "Pemimpin Kaum Beriman".[70] Jihadisme menjadi salah satu kelompok yang selalu dilawan dari dalam umat Islam di seluruh penjuru dunia yang dibuktikan dengan kehadiran hampir 2% populasi Muslim di London yang memprotes NIIS.[71] Mengikuti pendekatan yang lebih puritan dari Ibnu Katsir, Muhammad Rasyid Ridha, dll. banyak tafsir kontemporer mengabaikan signifikansi cerita Israiliyat, cerita yang bersumber dari Alkitab dan riwayat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setengah dari tafsir Arab menolak menggunakan cerita Israiliyat secara umum, sedangkan tafsir Turki biasanya sebagian membolehkan merujuk pada cerita Israiliyat. Akan tetapi, sebagian besar mufassir non-Arab menganggap Israiliyat tidak berguna atau tidak dapat diterapkan.[72] Rujukan langsung ke konflik Israel-Palestina tidak pernah ditemukan. Masih belum jelas apakah penolakan Israiliyat memiliki motif politik atau hanya sebatas pemikiran tradisionalis.[72] Penggunaan tafsir 'ilmi adalah karakteristik penting lainnya dari tafsir Sunni modern. Tafsir 'ilmi singkatan dugaan keajaiban ilmiah yang ditemukan dalam Al-Qur'an. Singkatnya, idenya adalah bahwa Al-Qur'an mengandung pengetahuan tentang hal-hal yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang penulis abad ke-7. Penafsiran semacam itu populer di antara banyak mufassir. Beberapa ulama mufassir Universitas Al-Azhar, menolak pendekatan ini, dengan alasan Al-Qur'an adalah teks untuk petunjuk agama, bukan untuk sains dan teori ilmiah yang dapat dibantah nantinya; dengan demikian tafsir 'ilmi dapat mengarah pada penafsiran yang keliru pada ayat-ayat Al-Qur'an.[73] Kecenderungan tafsir Islam modern umumnya dipandang untuk menyesuaikan dengan audiens modern serta memurnikan Islam dari dugaan perubahan, beberapa di antaranya diyakini sebagai bentuk tahrif yang sengaja dibawa ke dalam Islam untuk melemahkan dan merusak dakwahnya.[72] Penganut Sunni Para pengikut Sunni meyakini bahwa sahabat Muhammad adalah penyebar Islam yang andal, karena Allah dan Muhammad meridai mereka. Sumber abad pertengahan bahkan melarang kutukan atau fitnah mereka.[75] Keyakinan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Muhammad bersabda: "Yang terbaik dari manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka." Dukungan untuk pandangan ini juga ditemukan dalam Al-Qur'an, menurut Sunni.[76] Oleh karena itu, riwayat para sahabat juga diperhitungkan untuk pengetahuan iman Islam. Sunni juga percaya bahwa para sahabat adalah mukmin sejati karena para sahabatlah yang diberi tugas untuk memushafkan Al-Qur'an. Sunni tidak memiliki hierarki formal. Pemimpin agama bersifat nonformal, dan menuntut ilmu untuk menjadi ulama di bidang hukum (syariat) atau akidah (kalam). Kepemimpinan agama dan politik pada prinsipnya terbuka untuk semua umat Islam.[77] Menurut Islamic Center of Columbia, Carolina Selatan, setiap orang yang memiliki kecerdasan dan kemauan bisa menjadi ulama. Selama Salat Jumat, jemaah akan memilih orang berilmu untuk memimpin salat, yang dikenal sebagai khatib (orang yang berkhotbah).[78] Sebuah studi yang dilakukan Pew Research Center pada tahun 2010 dan dirilis Januari 2011 [79] menemukan bahwa terdapat 1,62 miliar Muslim di seluruh dunia, dan diperkirakan lebih dari 85–90% adalah Sunni.[80] Mazhab akidahTidak ada kesepakatan di antara para ulama mengenai bagaimana pandangan dogmatis yang harus dipegang oleh Sunni. Sejak periode modern awal, ada gagasan bahwa ada tiga mazhab akidah yang diakui sebagai Sunni:
Ulama Suriah Abdul-Baqi bin Faqih Fussa (w. 1661) menyebut kelompok tradisionalis ketiga ini mazhab Hambali.[81] Pemikir Ottoman İsmail Hakkı İzmirli (w. 1946), yang setuju untuk membagi Sunni menjadi tiga kelompok ini, menyebut kelompok ketiga ini sebagai "tradisionalis" atau "Salafiyah", tetapi juga menggunakan Atsariyah sebagai istilah alternatif. Untuk Maturidiyah dia memberikan Nasafiyah sebagai kemungkinan nama alternatif.[82] Istilah lain yang digunakan untuk kelompok berorientasi tradisionalis adalah "ahli hadis". Ini digunakan, misalnya, dalam dokumen akhir Muktamar Grozny. Hanya orang-orang "ahli Hadis" yang tergolong Sunni yang mempraktikkan tafwidh, yaitu yang menahan diri untuk tidak menafsirkan pernyataan-pernyataan Al-Qur'an yang rancu.[83] Asy'ariyahDigagas oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari (873–935), mazhab akidah ini dianut oleh banyak ulama dan terus berkembang di belahan dunia Islam sepanjang sejarah; al-Ghazali menulis tentang akidah yang membahasnya dan menyepakati beberapa prinsipnya.[84] Akidah Asy'ariyah menekankan wahyu ilahi atas akal manusia. Berbeda dengan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa etika tidak dapat diturunkan dari akal manusia, tetapi bahwa perintah Tuhan, sebagaimana diwahyukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (praktik-praktik Muhammad dan para sahabatnya sebagaimana dicatat dalam hadis), adalah satu-satunya sumber dari semua moralitas dan etika. Mengenai sifat-sifat Ketuhanan, Asy'ariyah menolak posisi Muktazilah bahwa semua rujukan Al-Qur'an tentang Allah beserta sifat-sifat-Nya adalah majaz (metafor). Kaum Asy'ari menganggap bahwa sifat-sifat ini adalah "sesuai dengan sifat Ketuhanan". Karena bahasa Arab merupakan bahasa yang luas mengingat satu kata dapat memiliki 15 arti yang berbeda, Asy'ariyah berusaha untuk menemukan makna yang paling sesuai dengan Allah tanpa bertentangan dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman, "Allah tidak serupa dengan sesuatu pun", ini jelas bermakna Allah tidak berjisim karena Dia-lah yang menciptakan bagian-bagian tubuh. Asy'ariyah cenderung menekankan kemahakuasaan ilahi atas kehendak bebas manusia dan mereka percaya bahwa Al-Qur'an itu abadi dan bukan makh |